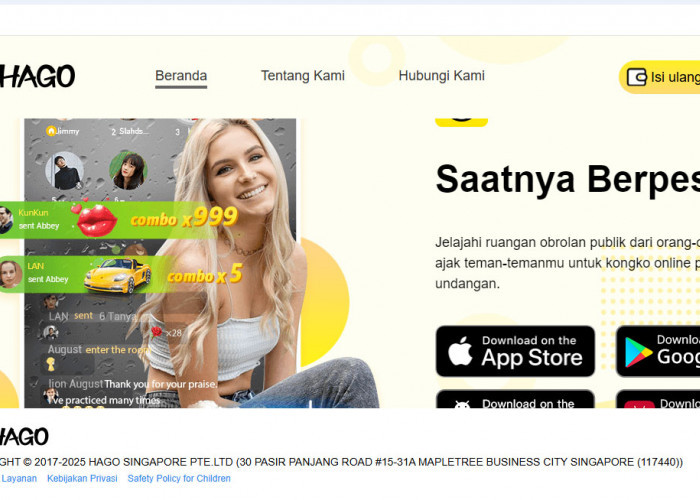Sawo Tegalsari

Joglonya di atas, menghadap ke gang sempit.
Rumah Anies di bawah, menghadap ke arah sungai Grogol. Atasnya menghadap ke barat. Bawahnya menghadap ke timur.
Saya datang langsung berhenti di dekat halaman joglo. Disediakan sedikit tanah di pinggir gang itu. Hanya cukup untuk meminggirkan satu mobil. Di situlah mobil saya parkir.
Saya pun melangkah ke halaman joglo. Melongok lewat lubang berteralis itu: ada kolam ikan di bawah sana.
Ada pula teras —bagian depan joglo. Dengan melewati teras, saya pun masuk joglo. Ada petugas yang menemani saya. Bisa menjelaskan banyak hal.
Perhatian saya tentu langsung ke apa yang diceritakan Pendeta Reno de Topeng: blandar gantung. Yakni blandar yang posisinya sekitar 1 meter di luar empat pilar utama joglo. Itulah yang membedakan joglo Tegalsari dengan joglo pada umumnya: blandar penyangga atap itu tidak bertumpu pada tiang satu pun.
Rumah kakek saya di Kebondalem, Tegalarum, Magaten, juga joglo. Kokoh. Dengan pohon sawo di sekitarnya. Tapi joglo kakek saya itu memang tidak ada blandar gantungnya.
Rumah tempat saya lahir hanya sepelemparan batu dari joglo itu. Saya selalu melewatinya saat berjalan menuju masjid. Kakek adalah kiai di masjid itu. Ayah saya menantu di situ. Hanya jadi imam pengganti.
Kalau bermain kami juga bermain di joglo itu. Atau di halamannya.
Setahun sekali, setiap Idul Fitri, seluruh keluarga besar berkumpul di joglo itu. Yakni setelah salat hari raya. Semua bersila melingkar di atas tikar. Yang laki-laki pakai sarung dan kopiah. Yang wanita pakai kain batik dan kebaya. Di kepala para wanita itu ada kerudung —yang umumnya dibiarkan jatuh di pundak. Belum ada budaya jilbab saat saya masih kecil.
Kakek dan nenek duduk di tempat paling sentral: di bawah talang yang memisahkan joglo dengan kamar tidur. Yang kecil-kecil, seperti saya, kebagian duduk di tikar nun jauh di dekat pintu keluar. Itu berarti saya harus berjalan sambil jongkok sangat jauh. Dilihat banyak orang: kalau cara saya laku dodok' salah bisa di-bully. Kami harus berjalan sambil dalam posisi ndodok —sedikit lebih tinggi dari duduk—menyeberangi hamparan tikar yang luas menuju tempat kakek-nenek duduk.
Tiba di depan kakek saya harus bersila. Lalu menangkupkan telapak tangan: menyembah kakek. Lalu mencium lutut kakek. Menyembah lagi —lalu beringsut ke depan nenek: menyembah, mencium lutut, menyembah, beringsut ke Pak De —yang duduk di sebelah nenek. Pun membuat gerakan yang sama. Beringsut lagi ke Pak De satunya. Dan satunya. Baru beringsut ke bapak saya, beringsut ke paman-paman. Ke sepupu yang lebih besar. Ke sekeliling joglo itu.
Anak sekarang bisa semaput kalau diikat dengan adat seperti itu.
Joglo menjadi seperti balai RW.
Pun joglo Tegalsari itu. Pun setelah dipindah ke Jakarta. Anies memfungsikannya sebagai arena publik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: