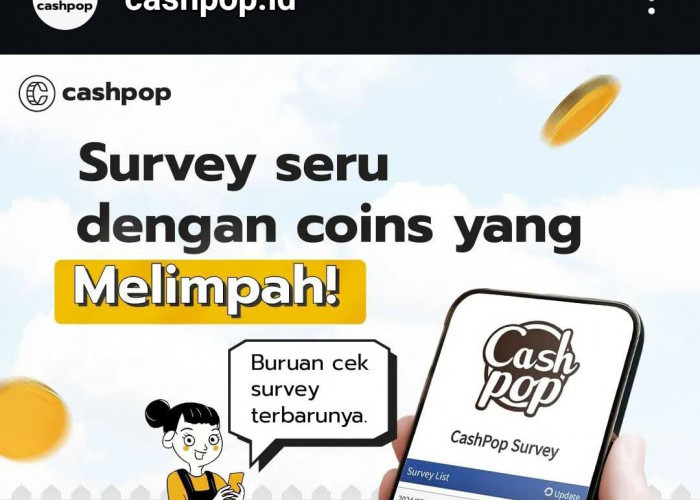Biaya Politik Mahal Bisa Jadikan Calon Tunggal di Pilkada

Sejumlah pihak menilai ada banyak faktor yang menyebabkan munculnya calon tunggal dalam Pilkada. Masalah yang paling utama di sistem demokrasi saat ini adalah mahalnya biaya politik.
Diprediksi, tidak banyak parpol maupun calon yang berani bertaruh di kontestasi Pilkada tersebut. Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo menyebut, calon tunggal dalam Pilkada juga akibat proses politik yang tidak cukup dan hal itu yang tidak terbangun di banyak daerah.
Ia menambahkan, tidak adanya calon dengan reputasi pribadi dan politik yang dikenal oleh masyarakat di suatu daerah yang melakukan pemilihan kepala daerah. "Karena modal banyak uang saja tidak cukup untuk bertarung di pilkada," ujar Arif di Jakarta, Senin (10/8).
Diberitakan sebelumnya, calon tunggal pada Pilkada 2020 yang akan dihelat di 270 daerah diprediksi mengalami peningkatan menjadi 31 daerah atau hampir 2 kali lipat dari Pilkada 2018 yang berjumlah 16.
Perludem memperkirakan, calon tunggal melawan kotak kosong akan terjadi di 31 daerah pada Pilkada 2020 mendatang. Daerah potensial itu terdiri dari 26 kabupaten dan lima kota dari 270 daerah yang menggelar Pilkada serentak tahun ini.
Meski demikian, Perludem menilai hal ini masih bisa berubah karena masih sangat dinamis. Proses pencalonan dalam Pilkada sendiri terkadang cenderung injury time.
Arif melanjutkan, pemerintah juga perlu membentuk Lembaga Peradilan Pemilu, mengingat banyaknya masalah yang kerap terjadi dalam pelaksanaan Pemilu. "Tak hanya menyangkut pelanggaran pidana dalam Pemilu, lembaga ini juga kelaknya akan mengatur hukum politik Indonesia," imbuhnya.
Dia Arif memaparkan mengenai fungsi dan tugas Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Dikatakannya, DKPP merupakan suatu lembaga ajudifikasi Pemilu yang sifatnya hanya mengadili etik terkait Pemilu.
"Saya ingin mengatakan DKPP memang dibatasi menjadi semacam lembaga ajudifikasi. Hanya untuk peradilan etik saja. Lebih dari peradilan etik tidak dimungkinkan. Karena dalam undang-undang sudah mengatur kalau ada masalah dalam hal pelanggaran sifatnya administratif, disampaikan oleh pihak mana, bagaimana hukumnya, dan seterusnya. Tidak menyangkut pelanggaran pidana dan sebagainya," ucapnya.
Karena DKPP sifatnya hanya mengatur etik saja, maka kemungkinan diperlukan pembentukan lembaga peradilan Pemilu yang akan mengatur hukum politik Indonesia. "Saya kira ke depan soal DKPP yang kemudian hari-hari ini isunya didorong. Karena memang UU sudah menyediakan UU 10 Tahun 2016, agar ke depan jika memungkinkan, dan ini tentu bagian politik hukum kita ke depan adalah mengenai pembentukan Lembaga Peradilan Pemilu," papar Arif.
Menurutnya, masih diperlukan pembahasan lebih lanjut terkait wacana ini. Ia juga mengimbau agar Indonesia mencontoh negara-negara yang telah menerapkan sistem lembaga peradilan Pemilu.
"Problem etik yang terjadi pada penyelenggara memang diadili DKPP, dimana unsur di dalamnya adalah pihak penyelenggara, dan lainnya tokoh masyarakat untuk menguji. Apakah penyelenggara itu bisa dibuktikan secara hukum, dan memang tidak diberikan ruang pada pelanggaran bukan etik. Saya kira penting kita bicara lebih lanjut tentang keberadaan DKPP," tukas politisi PDIP itu.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. "Ini menurut saya merupakan preseden buruk dalam rangka pendidikan politik dan pendidikan demokrasi," kata Guspardi di Jakarta, Senin (10/8).
Guspardi mengatakan, Pilkada adalah kompetisi tentang visi dan misi antar kepala daerah. Banyaknya calon tunggal tersebut menyebabkan tidak terwujudnya substansi Pilkada. "Karena yang dihadapi kotak, kotak artinya dia tidak punya otak, dia tidak punya visi dan misi. Padahal kita punya penduduk terbesar, empat terbesar dunia," ungkapnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: